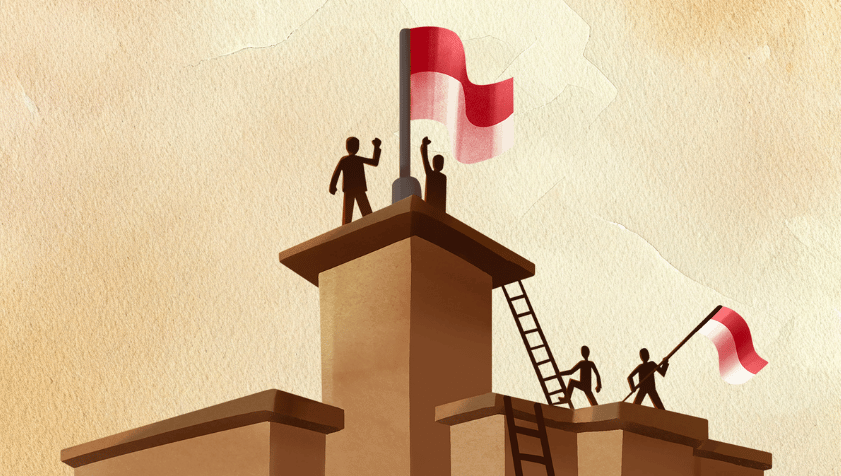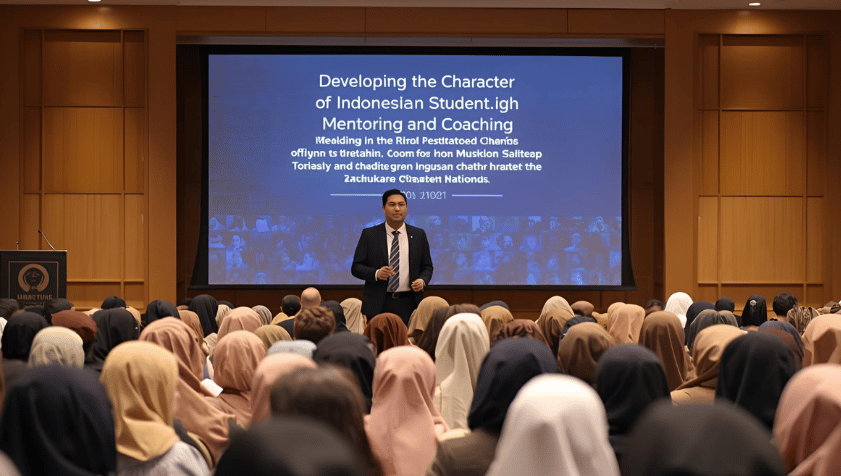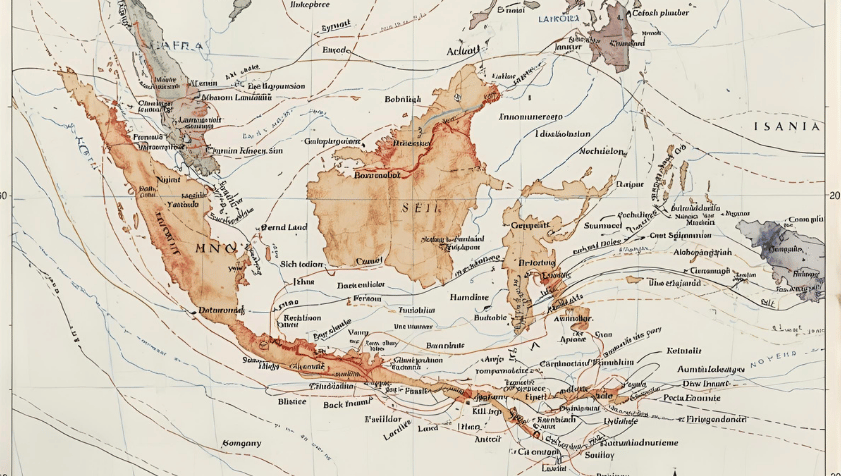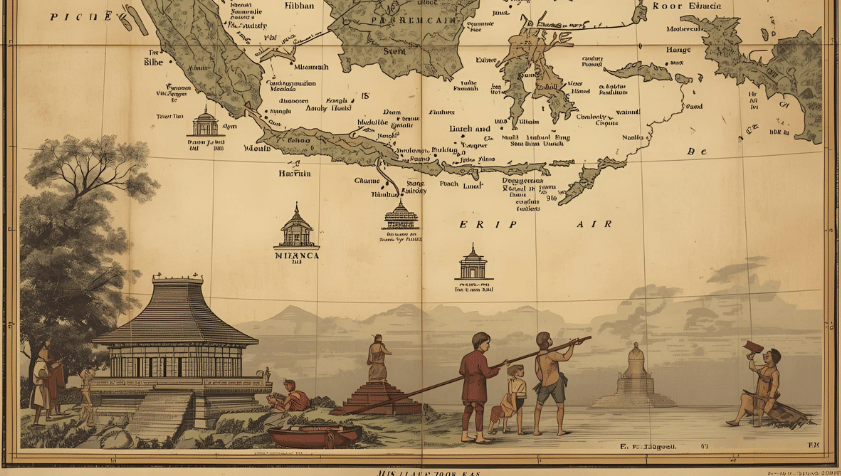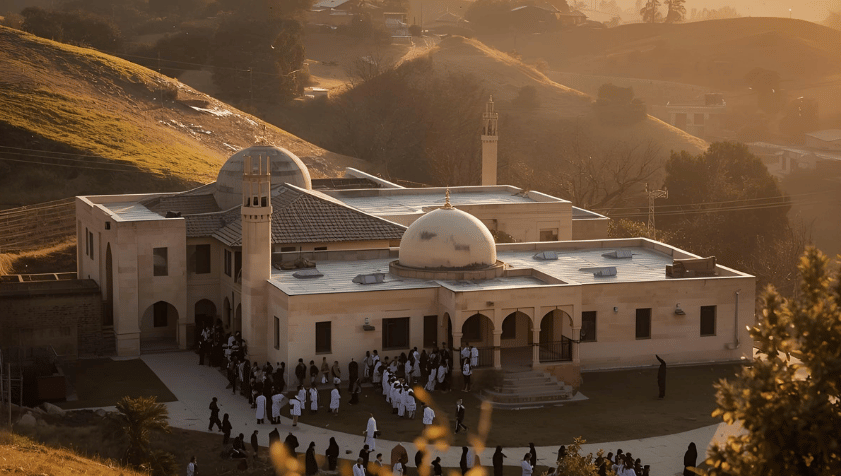Dalam lanskap sejarah dan sosiologi Indonesia, istilah “Santri” dan “Nasionalisme” sering kali diletakkan dalam dua kutub perbincangan yang berbeda. Namun, realitas keindonesiaan membuktikan bahwa kedua entitas ini memiliki hubungan simbiosis yang sangat erat, organik, dan tak terpisahkan. Hubungan santri dan nasionalisme di Indonesia bukan sekadar fenomena politik tempelan, melainkan sebuah manifestasi iman yang mengakar kuat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa.
Narasi bahwa agama dan negara adalah dua hal yang bertentangan sering kali dipatahkan oleh rekam jejak kaum sarungan di Nusantara. Bagi seorang santri, mencintai tanah air adalah konsekuensi logis dari keimanan. Artikel ini akan mengupas secara tuntas bagaimana konstruksi nasionalisme terbentuk dalam tradisi pesantren, peran vital santri dalam mempertahankan kedaulatan negara, hingga relevansi nilai-nilai tersebut di era disrupsi digital saat ini. Memahami hubungan ini sangat penting untuk melihat wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan inklusif.
Definisi dan Identitas: Siapakah Santri dalam Konteks Kebangsaan?
Secara etimologi dan kultural, santri merujuk pada seseorang yang sedang menuntut ilmu agama Islam di lembaga pendidikan pesantren di bawah bimbingan seorang Kiai. Namun, dalam konteks sosiologi kebangsaan, definisi santri meluas menjadi sebuah identitas budaya dan sosial. Clifford Geertz dalam The Religion of Java mengkategorikan santri sebagai kelompok Muslim yang taat menjalankan syariat.
Namun, dalam bingkai nasionalisme, santri adalah garda terdepan yang memiliki karakteristik unik: mereka memiliki kepatuhan religius yang tinggi sekaligus loyalitas tanpa syarat terhadap tanah air tempat mereka berpijak. Identitas santri tidak lepas dari budaya lokal (local wisdom). Inilah yang membedakan santri di Indonesia dengan pelajar agama di Timur Tengah. Santri Indonesia diajarkan untuk merawat tradisi sembari mengadopsi nilai-nilai modernitas yang relevan, sebuah prinsip yang dikenal dengan Al-Muhafadzatu ‘ala qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah (Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).
Dalam konteks kebangsaan, santri adalah representasi dari masyarakat sipil yang mandiri. Pesantren sebagai basis santri telah ada jauh sebelum sistem pendidikan formal kolonial Belanda didirikan. Oleh karena itu, santri memiliki legitimasi historis sebagai “pemilik sah” republik ini, yang membuat rasa nasionalisme mereka tumbuh secara natural, bukan karena indoktrinasi negara.
Akar Sejarah: Perlawanan Santri Melawan Kolonialisme
Membahas hubungan santri dan nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perlawanan terhadap penjajah. Jauh sebelum kata “Indonesia” dikumandangkan, jaringan santri dan ulama telah melakukan perlawanan sengit terhadap hegemoni VOC dan pemerintah Hindia Belanda.
Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro adalah bukti nyata keterlibatan kaum santri. Pangeran Diponegoro sendiri adalah sosok yang lekat dengan tradisi santri. Para pengikutnya, yang disebut sebagai Kiai Mojo dan pasukannya, adalah basis massa santri yang militan. Motivasi mereka bukan hanya membebaskan wilayah dari pajak dan penindasan kolonial, tetapi juga Jihad fi Sabilillah untuk menegakkan keadilan.
Pada awal abad ke-20, kebangkitan nasional juga dimotori oleh kaum santri. Berdirinya Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Sarekat Islam) pada tahun 1905 oleh H. Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto menandai fase baru nasionalisme santri yang lebih terorganisir secara modern. Organisasi ini menjadi wadah politik pertama yang secara tegas melawan ketidakadilan ekonomi dan politik kolonial dengan basis massa Islam yang besar.
Selanjutnya, berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 dan Muhammadiyah pada tahun 1912 semakin mempertegas posisi Islam dalam kebangsaan. KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari menanamkan fondasi bahwa memajukan umat melalui pendidikan dan sosial adalah bagian dari upaya memerdekakan bangsa dari kebodohan dan keterbelakangan, yang merupakan “penjajahan” dalam bentuk lain.
Resolusi Jihad: Titik Kulminasi Nasionalisme Santri
Salah satu momen paling monumental dalam sejarah hubungan santri dan nasionalisme adalah peristiwa “Resolusi Jihad” yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945. Peristiwa ini sering kali luput dari buku sejarah formal selama beberapa dekade, namun kini diakui sebagai tonggak penting yang melahirkan peringatan Hari Santri Nasional.
Ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, tentara Sekutu (NICA) berusaha kembali menguasai tanah air. Presiden Soekarno saat itu mengirim utusan untuk bertanya kepada KH Hasyim Asy’ari mengenai hukum membela tanah air (bukan membela agama semata). Jawaban dari Rais Akbar PBNU tersebut sangat tegas dan menggemparkan.
Pada tanggal 22 Oktober 1945, para ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai Resolusi Jihad. Isi pokok dari resolusi ini adalah:
-
Hukum memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia adalah Fardhu ‘Ain (kewajiban individu) bagi setiap Muslim yang berada dalam radius 94 km dari tempat kedudukan musuh.
-
Hukum bagi mereka yang berada di luar radius tersebut adalah Fardhu Kifayah (kewajiban kolektif).
Fatwa ini menjadi bahan bakar utama yang memicu Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ribuan santri dan kiai turun ke medan perang dengan persenjataan seadanya, digerakkan oleh keyakinan bahwa mati dalam membela tanah air adalah mati syahid. Peristiwa ini adalah bukti empiris bahwa bagi santri, nasionalisme bukan sekadar retorika, melainkan diletakkan setara dengan kewajiban agama.
Hubbul Wathan Minal Iman: Landasan Teologis Nasionalisme Santri
Mengapa santri begitu mencintai Indonesia? Jawabannya tidak hanya terletak pada fakta sosiologis bahwa mereka lahir di sini, tetapi juga pada landasan teologis yang kuat. Doktrin Hubbul Wathan Minal Iman (Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman) telah terinternalisasi dalam kurikulum kehidupan pesantren.
Meskipun ungkapan ini sering diperdebatkan validitasnya sebagai hadis Nabi oleh para ahli hadis, namun secara substansi (makna), para ulama sepakat bahwa mencintai tanah air adalah anjuran agama. KH Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU, mempopulerkan jargon ini melalui lagu Syubbanul Wathan (Pemuda Cinta Tanah Air) pada tahun 1934, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Secara fiqih, menjaga kedaulatan negara adalah bagian dari Hifdzul Ardli (menjaga kehormatan wilayah) dan Hifdzun Nafs (menjaga jiwa). Tanpa negara yang aman dan berdaulat, umat Islam tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Oleh karena itu, keberadaan negara (nasionalisme) menjadi prasyarat bagi terlaksananya syariat agama (religiusitas).
Dalam pandangan santri, Indonesia disebut sebagai Darul Mistaq (Negara Kesepakatan) atau Darus Salam (Negara Damai), bukan Darul Islam (Negara Islam secara formal). Kesepakatan ini merujuk pada konsensus para pendiri bangsa untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila. Menghormati kesepakatan adalah kewajiban agama, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menghormati Piagam Madinah yang mengatur hubungan antara Muslim, Yahudi, dan kaum pagan di Madinah.
Penerimaan Asas Tunggal Pancasila: Kedewasaan Politik Kaum Santri
Ujian terbesar hubungan santri dan nasionalisme terjadi pada masa perumusan dasar negara dan periode Orde Baru. Pada sidang BPUPKI dan PPKI, tokoh-tokoh santri seperti KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo menunjukkan kenegarawanan yang luar biasa.
Demi keutuhan bangsa dan agar wilayah Indonesia Timur tidak memisahkan diri, para tokoh Islam ini bersedia menghapus “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta (“…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”). Penghapusan ini adalah pengorbanan ideologis terbesar kaum santri demi persatuan nasional (Nasionalisme). Mereka menyadari bahwa substansi nilai Islam (Keadilan, Ketuhanan, Persatuan) sudah terwakili dalam Pancasila tanpa perlu label formal syariat.
Puncak dari integrasi Islam dan Nasionalisme terjadi pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, di mana kaum santri secara resmi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Keputusan ini, yang dimotori oleh KH Achmad Siddiq, menegaskan bahwa Pancasila adalah bentuk final dari negara Indonesia. Tidak ada lagi pertentangan antara menjadi Muslim yang taat dan menjadi warga negara Indonesia yang setia. Penerimaan ini menutup celah bagi ideologi transnasional yang ingin mengubah bentuk negara, menjadikan santri sebagai benteng utama NKRI.
Pesantren sebagai Laboratorium Nasionalisme
Bagaimana nasionalisme diajarkan di lingkungan pesantren hari ini? Pesantren modern maupun salaf (tradisional) memiliki metode unik dalam menanamkan rasa cinta tanah air yang berbeda dengan sekolah umum.
-
Kurikulum Kewarganegaraan Berbasis Fiqih: Di pesantren, diajarkan kitab-kitab Fiqh Siyasah (Politik Islam) yang membahas tentang kewajiban taat kepada pemimpin yang sah (Waliyul Amri) selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Ini membangun kesadaran hukum dan ketertiban.
-
Kehidupan Komunal yang Majemuk: Pesantren adalah miniatur Indonesia. Santri datang dari berbagai suku, bahasa, dan latar belakang budaya. Mereka tidur, makan, dan belajar bersama dalam satu asrama. Interaksi ini secara alami menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) yang merupakan inti dari nasionalisme Indonesia.
-
Upacara dan Simbol Negara: Saat ini, hampir seluruh pesantren rutin melaksanakan upacara bendera, terutama pada hari Senin dan hari besar nasional. Penghormatan kepada bendera Merah Putih tidak lagi dianggap sebagai bid’ah atau syirik, melainkan sebagai bentuk penghormatan (takzim) kepada simbol kedaulatan negara.
-
Doa untuk Bangsa: Tradisi istighosah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa adalah rutinitas di pesantren. Ini adalah bentuk nasionalisme spiritual; di mana santri “mengetuk pintu langit” demi kedamaian di bumi pertiwi.
Santri Milenial: Nasionalisme di Era Digital dan Tantangan Radikalisme
Memasuki abad ke-21, tantangan nasionalisme bergeser dari kolonialisme fisik ke kolonialisme ideologi dan ekonomi. Di era disrupsi informasi, muncul fenomena radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama untuk merongrong negara. Kelompok-kelompok ini sering membenturkan konsep Khilafah dengan NKRI.
Di sinilah peran strategis “Santri Milenial”. Generasi santri baru yang melek teknologi memiliki tugas ganda: memperdalam ilmu agama dan menguasai narasi digital. Santri menjadi “Firewall” atau tembok api yang menghalau paham-paham radikal.
Konsep Wasathiyah (Moderasi Beragama) yang diusung oleh kaum santri menjadi antitesis dari ekstremisme. Santri mengajarkan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Melalui platform media sosial, website, dan konten kreatif, para santri menyebarkan narasi bahwa membela negara adalah jihad konstitusional.
Selain itu, nasionalisme santri kini juga merambah ke sektor ekonomi dan kemandirian. Munculnya gerakan “Santripreneur” menunjukkan bahwa nasionalisme juga berarti membangun kekuatan ekonomi umat agar tidak bergantung pada produk asing. Kemandirian ekonomi pesantren adalah wujud nyata kedaulatan ekonomi bangsa.
Kesimpulan
Hubungan santri dan nasionalisme di Indonesia adalah hubungan yang bersifat historis, teologis, dan strategis. Sejarah membuktikan bahwa tanpa peran santri dan ulama, kemerdekaan Indonesia mungkin akan memiliki cerita yang berbeda. Dari Perang Diponegoro hingga Resolusi Jihad, darah santri telah tumpah untuk menyatukan ribuan pulau menjadi satu bangsa.
Secara teologis, doktrin Hubbul Wathan Minal Iman telah menempatkan cinta tanah air sebagai manifestasi kesalehan. Seorang santri yang baik pastilah warga negara yang baik, dan warga negara yang baik—jika ia Muslim—seharusnya meneladani semangat santri.
Di masa depan, peran santri akan semakin krusial dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi dan radikalisme. Pesantren harus tetap menjadi kawah candradimuka yang mencetak kader bangsa yang berotak London (berwawasan global) tapi berhati Masjidil Haram (berkarakter religius). Sinergi antara nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang diperjuangkan kaum santri adalah modal sosial terbesar yang dimiliki bangsa ini untuk melangkah menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber Referensi
-
Bruinessen, M. van. (1995). Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.
-
Burhanudin, J. (2012). Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia. Jakarta: Mizan Publika.
-
Fealy, G. (2003). Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKiS.
-
Geertz, C. (1960). The Religion of Java. Glencoe: The Free Press.
-
Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
-
Noer, D. (1973). The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900–1942. Singapore: Oxford University Press.
-
PBNU. (1945). Teks Resolusi Jihad. Arsip Nasional Republik Indonesia.
-
Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.
-
Steenbrink, K.A. (1984). Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen. Jakarta: LP3ES.
-
Wahid, A. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute.